
LIPUTAN KHUSUS:
Jejak Emisi Batu Bara di Kendaraan Listrik
Penulis : Sadam Afian R., Fattia Syavira, Peneliti Auriga Nusantara
Kebutuhan nikel untuk bahan baterai kendaraan listrik masih bergantung pada batu bara, penyumbang emisi.
OPINI
Selasa, 01 November 2022
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Kendaraan listrik sebagai salah satu transportasi alternatif rendah emisi terus tumbuh dalam beberapa tahun belakangan. Kendaraan rendah emisi ini menyisakan masalah, kebutuhan nikel –sebagai salah satu bahan baterai kendaraan listrik– masih bergantung pada batu bara, penyumbang emisi terbesar.
Tren kendaraan listrik meningkat seiring dengan isu energi bersih. Kendaraan ini dapat menghasilkan emisi lebih rendah dan lebih efisien sebesar 3-5 kali dibandingkan dengan penggunaan kendaraan dengan bahan bakar fosil.
Data Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menunjukkan angka produksi kendaraan listrik dari tahun 2019 terus meningkat. Sedangkan International Energy Agency (IEA), peningkatan penjualan mobil listrik yang awalnya sebesar 17.000 pada tahun 2010, kini meningkat sebanyak 7,2 juta kendaraan pada 2019. Dan pada 2030 diprediksi sebesar 140 juta kendaraan listrik akan digunakan secara global.
Hal inilah yang membuat nikel, bahan baku baterai kendaraan listrik, digadang sebagai energi bersih dunia. Pada tahun yang sama, permintaan nikel secara global mencapai 5-8 persen untuk kebutuhan baterai atau sebesar 162 kiloton dan dapat meningkat hingga 265 kiloton pada 2030.

Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar tentu turut berkontribusi dalam transisi penggunaan energi ini. AEER mencatat sebesar 37,04 persen dari total cadangan dunia berada di Indonesia, Tiga provinsi terbesar dengan cadangan nikel tersebar di Sulawesi Tenggara (32 persen), Maluku Utara (27 persen), dan Sulawesi Tengah (26 persen).
Potensi besar nikel ini mendorong pemerintah menggenjot pengolahan bijih nikel di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak tahun 2009 hingga sekarang. UU Minerba Nomor 4/2009, industri nikel didorong untuk segera memiliki fasilitas pemurnian demi meningkatkan nilai ekonomi dari nikel sendiri. Paket-paket regulasi diterbitkan hingga industri pertambangan di Indonesia tidak lagi mengekspor bijih nikel mentah melainkan ekspor dalam bentuk olahan.
Hingga tahun 2021, Kementerian ESDM mencatat terdapat 21 smelter yang telah beroperasi. Angka tersebut terus digenjot oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan stimulan seperti memberikan insentif perpajakan hingga prioritas pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada tahun ini, Pemerintah menargetkan 7 smelter tambahan yang terbangun. Dari jumlah tersebut, 3 dari 7 smelter sudah memiliki progres di atas 98 persen.
Industri pengolahan nikel di Indonesia tersebar di beberapa provinsi, yaitu Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah yang dekat dengan sumber bijih nikel. Secara proyeksi, ke depan smelter nikel juga akan dibangun di wilayah-wilayah tersebut.
Secara umum, proses bisnis pengolahan nikel dilakukan dengan mesin rotary yang membutuhkan daya yang besar. Daya tersebut bersumber dari pembangkit listrik, baik yang dibangun oleh perusahaan smelter itu sendiri maupun pembangkit yang telah dibangun oleh PLN. Kebutuhan daya listrik yang besar tersebut digunakan untuk melakukan operasional pengolahan dan pemurnian bijih nikel.
Berdasarkan data Kementerian ESDM pada 2019, jumlah pembangkit listrik untuk smelter tercatat sebanyak 68 pembangkit yang terbagi atas smelter konsentrat & lumpur anoda (16 smelter), nikel (41 smelter) dan bauksit (11 smelter). Kebutuhan pembangkit listrik untuk smelter yang tersebar di beberapa provinsi terbilang besar. Tiga provinsi dengan kebutuhan tenaga listrik untuk smelter terbesar seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara tercatat masih membutuhkan pembangkit listrik bertenaga uap.
Tidak dipungkiri, sampai saat ini sejumlah 126 pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar fosil, terutama batu bara. Berdasarkan data ESDM, pada 2021, dari total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia sebesar 73.688 MW, terpasang 36.976 MW atau 50% bersumber dari pembangkit listrik batu bara (PLTU). Kapasitas ini menunjukkan pembangkit listrik di Indonesia setengahnya bersumber dari batu bara dan mendudukkan Indonesia sebagai negara dengan produksi batu bara terbesar ketiga di dunia. Hingga saat ini, jumlah produksi batu bara mencapai 614 juta ton dan konsumsi batu bara mencapai 133 juta ton.
Data-data tersebut menunjukkan bahwa pasokan batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik smelter sangat besar. Hal ini tentu saja bertentangan dengan cita-cita nikel sebagai salah satu alternatif energi bersih. Kebutuhan yang besar terhadap batubara tentu membuat pembukaan lahan untuk penambangan batubara juga besar. Selain pada proses pertambangan, limbah tailing industri batubara juga menjadi persoalan yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan.
Selain itu, dilihat dari kebersihan udara, pembangkit batubara menjadi pemicu berbagai penyakit pernafasan berbahaya.
Salah satu contohnya, pada industri pengolahan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Utara, limbah PLTU untuk smelter membuat air lautan panas dan membuat nelayan tidak bisa berkegiatan di daerah Lolaro, yang dulunya merupakan daerah tangkapan ikan. Aktivitas kapal tongkang yang membawa suplai batu bara serta debu batu bara dari PLTU juga mempengaruhi penurunan tangkapan. Selain itu, akibat lalu lintas kapal tongkang yang mengangkut batubara untuk pasokan PLTU, aktivitas nelayan juga menjadi terganggu. Padahal masyarakat di daerah Halmahera Tengah banyak menggantungkan kehidupan mereka dari hasil tangkapan ikan.
Meski begitu, peneliti sendiri hingga saat ini belum mendapatkan data yang rinci terkait pasokan batubara ke pembangkit smelter. Akses data ini tidak dibuka, padahal dengan kebutuhan bahan baku yang besar, penting untuk mengetahui distribusi dan volume batubara. Data ini demi memastikan industri berjalan dalam koridor yang dapat meminimalisir dampak buruk lingkungan akibat penggunaan batubara.
Kelak perlu kebijakan-kebijakan terkait proses bisnis industri hilir yang lebih memperhatikan aspek lingkungan. Akan menjadi percuma jika di hulu, pihak-pihak memperketat dampak deforestasi, namun di hilir justru menggunakan energi kotor yang sejak lama didorong untuk ditinggalkan.
Alternatif penggunaan pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan seperti pembangkit tenaga air juga harus terus didorong. Apalagi pemenuhan energi hijau terus dilakukan PLN sesuai sertifikat EBT atau Renewable Energy Certificate (REC). Produksi dan pengolahan nikel tentu harus memenuhi angan tersebut. Penggunaan energi bersih dalam pengolahannya menjadi salah satu poin penting, tentu di samping menekan deforestasi di sektor hulu.


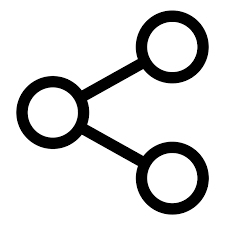 Share
Share

