Alasan COP26 Krusial Untuk Nasib Manusia, Iklim juga Indonesia
Penulis : Kennial Laia
Perubahan Iklim
Selasa, 26 Oktober 2021
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Konferensi iklim atau Conference of Parties ke-26 (COP26) di Glasgow, Skotlandia, semakin dekat. Negosiasi negara-negara yang hadir akan menjadi ujung tombak penentu arah kebijakan dan upaya dalam menghadapi pemanasan global.
Agenda tahunan ini menjadi penting setelah Perjanjian Paris yang dihasilkan dalam COP21 pada 2015. Sebanyak 197 negara yang hadir bersepakat untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 1.5C hingga akhir abad ini. Komitmen itu kemudian tertuang dalam Nationally Determined Contributions (NDCs) masing-masing negara.
Lewat kerangka bersama ini, negara-negara di dunia berjanji untuk menyusun rencana penurunan emisi karbon secara signifikan untuk mencapai target tersebut. Rancangan ini akan dibawa pada COP26, lima tahun setelah kesepakatan.
Lebih dari 100 negara telah berkomitmen untuk mencapai emisi net zero, termasuk negara penghasil emisi terbesar seperti Cina, Amerika Serikat, dan Inggris. Indonesia juga telah mengumumkan target net zero pada 2058 atau lebih cepat.
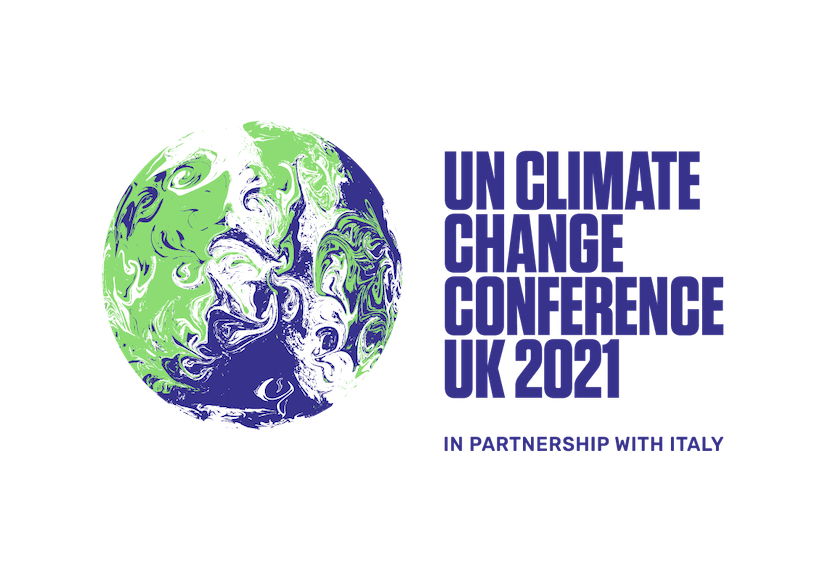
Sebelumnya Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) mengungkap bahwa target iklim 75 negara-negara di dunia dalam NDCs terbarunya tidak sejalan dengan target dalam Perjanjian Paris.
Namun, barangkali ini akan menjadi kesempatan bagi para pemimpin dunia untuk menghasilkan sebuah keputusan yang berpihak pada penanganan krisis iklim yang serius.
Sebelumnya laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) telah memperingatkan bahwa dunia hanya punya waktu hingga 2030 untuk mencegah dampak katastrofik dari krisis iklim.
Saat ini peringatan tersebut semakin nyata, terlihat dari berbagai bencana terkait perubahan iklim yang terjadi di berbagai wilayah. Banjir bandang di kontinen Eropa, pandemi Covid-19, gelombang panas ekstrem dan kebakaran hutan di berbagai wilayah, pencairan es di kutub, kenaikan permukaan air laut, hingga kekeringan di Afrika bagian selatan yang terjadi sejak 2018.
Untuk menghindari bencana ini, negosiasi pada COP26 harus berhasil. Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara Tata Mustasya mengatakan, kunci keberhasilan konferensi tersebut adalah perubahan paradigma negara peserta.
“Harus ada kesadaran bersama bahwa kita tidak bisa lagi membangun ekonomi dengan cara yang sama, yang selama ini hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dengan merusak lingkungan,” kata Tata kepada Betahita, Senin, 25 Oktober 2021.
Jika hal tersebut disepakati, negara-negara juga harus melakukan transisi hijau dengan pembangunan rendah karbon, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pembangunan inklusif.
“Karena sebagian besar emisi global juga berasal dari sektor energi, transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi bersih dan terbarukan merupakan kunci,” jelas Tata.
Kunci lainnya adalah kepemimpinan negara ekonomi besar seperti Amerika Serikat dan Cina (sekaligus penghasil emisi terbesar) dalam mendorong transisi ke ekonomi hijau secara global. Peran swasta juga krusial dalam menentukan perubahan ini.
“Penting juga buat negara berkembang dan miskin memiliki suara bersama mengenai keadilan iklim ini. Indonesia dalam hal ini harusnya bisa memainkan peran ini,” jelas Tata.
Poin-poin negosiasi
Konferensi iklim ini akan dimulai pada 31 Oktober hingga 12 November. Topik utama pembahasan dan negosiasi dalam konferensi ini adalah bagaimana menentukan arah dari aspek-aspek kunci mengenai penanganan pemanasan global.
Salah satu pembahasan utama adalah bagaimana komitmen dan implementasi negara-negara di bawah Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu bumi pada 1.5C, atau 2C. Dengan situasi yang semakin genting, ada kemungkinan negara-negara akan diminta untuk menaikkan ambisi.
Isu lainnya adalah pembiayaan kepada negara berkembang dalam penanganan iklim yang disediakan oleh negara kaya dan penghasil emisi terbesar di dunia. Adaptasi terhadap perubahan iklim dan kebijakan terkait perdagangan karbon juga akan masuk dalam agenda.
Penghasil emisi terbesar juga akan dibutuhkan untuk mendukung negara-negara berkembang terkait pembiayaan dan pengadaan teknologi untuk memungkinkan mereka melakukan transisi pada energi bersih dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, termasuk banjir besar dan kekeringan panjang.
Dalam hal ini, negara maju harus membuktikan komitmen untuk pendanaan iklim minimal USD 100 miliar atau lebih. “Penting juga negara-negara maju juga tidak menggunakan pendanaan ini untuk carbon offsetting. Mereka harus beralih ke ekonomi hijau,” sebut Tata.
Tata juga mengingatkan agar negara maju tidak menggunakan pendanaan tersebut sebagai carbon offsetting lantaran dapat memperburuk ketidakadilan ekonomi global. Konsep ini mencakup peniadaan emisi CO2 yang dihasilkan di satu tempat dengan tindakan pengurangan emisi di tempat lain.
“Namun pada saat bersamaan negara-negara berkembang juga harus melakukan transisi hijau dan mengambil peluang bisnis, lapangan kerja, dan pembangunan yang lebih inklusif dari tren global dan kesepakatan dalam COP,” pungkas Tata.
Apa itu net zero?
Target emisi net zero juga menjadi topik negara-negara yang membawa rencana penurunan emisi mereka ke COP26.
Net zero artinya tidak menambah jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Gas beracun ini, seperti karbon dioksida (CO2) dilepaskan dari aktivitas yang melibatkan pembakaran minyak, gas, dan batu bara. Sektornya termasuk rumah tangga, pabrik/manufaktur, dan transportasi. Emisi yang dihasilkan kemudian menjebak energi matahari di atmosfer, dan menyebabkan pemanasan global.
Untuk mencapai net zero, reduksi emisi gas rumah kaca sebanyak mungkin sangat krusial, serta menyeimbangkan jumlah yang tersisa dengan menghilangkan jumlah yang setara.
Di bawah Perjanjian Paris pada 2015, 197 negara menyepakati untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 1.5C untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim.
Berbagai ilmuwan juga mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, dunia harus mengurangi emisi CO2 menjadi net zero pada 2050. Hal ini yang kemudian akan menjadi topik utama dalam negosiasi pada COP26 di Glasgow, Skotlandia, Oktober mendatang.
Namun, tidak semua emisi dapat dikurangi menjadi nol. Karena itu jumlah yang tersisa akan dikompensasi atau diimbangi (carbon offsetting). Salah satu caranya adalah menggunakan teknologi seperti carbon capture and storage (CCS).
Metode ini menggunakan mesin yang menghilangkan karbon dari udara. Karbon kemudian dipadatkan lalu dikubur di bawah tanah. Namun teknologinya masih dalam pengembangan, sangat mahal, dan belum terbukti khasiatnya.
Bagaimana dengan Indonesia?
Tata menyebut kunci zero emission pada 2050 harus sudah terlihat pada 2030. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda menuju ke arah tersebut. Di sektor kelistrikan, misalnya, tidak ada negara di Asia Tenggara yang berada pada jalur 1,5C, termasuk Indonesia.
Indonesia telah menyerahkan dokumen NDC, dengan target iklim meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan komunitas internasional pada 2030.
Dalam dokumen NDC terbaru, Indonesia juga menyerahkan Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam pembaruan itu, Indonesia mengubah target pengurangan emisi. Walau berbagai kritik menilai target itu belum sejalan dengan target Perjanjian Paris dan mendorong Indonesia agar lebih ambisius menetapkan targetnya.
Menurut Tata, saat ini Indonesia belum berada pada jalur 1,5C karena hanya akan mencapai porsi 26 persen energi bersih terbarukan dari total 50 persen yang dihitung IPCC jika ingin berada di jalur tersebut.
Skenario terbaik bagi Indonesia di sektor energi terbarukan adalah Indonesia berhenti membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara baru. Sebaliknya pemerintah diharapkan hanya membangun generator bertenaga surya dan angin.
“Kabar baiknya, jika dilakukan perubahan mendasar dalam regulasi dan kebijakan Indonesia bisa berada di jalur yang tepat di 2050 untuk sektor kelistrikan. Poinnya baik menuju 2030 dan 2050, memang dibutuhkan perubahan fundamental dalam cara membangun jika ingin berada di jalur yang tepat. Tidak bisa setengah hati,” ujar Tata.



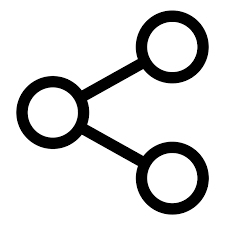 Share
Share

